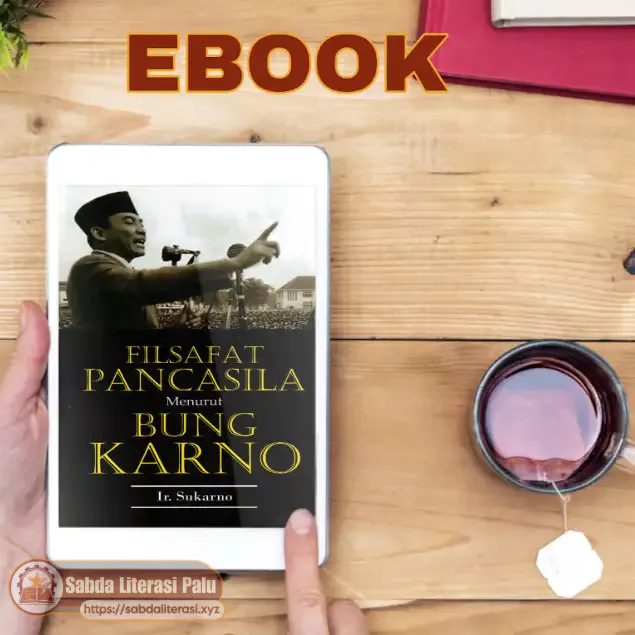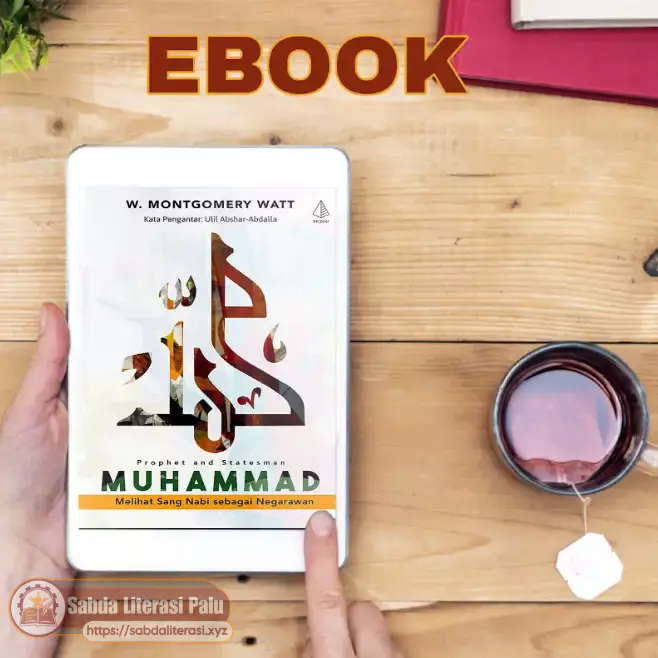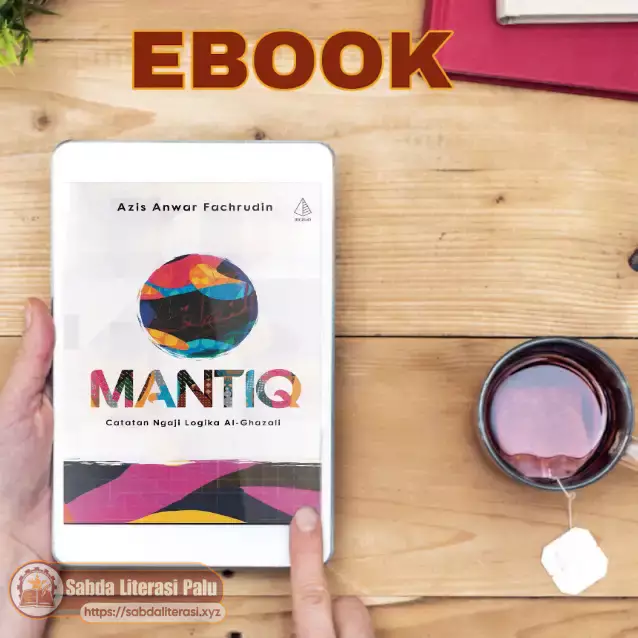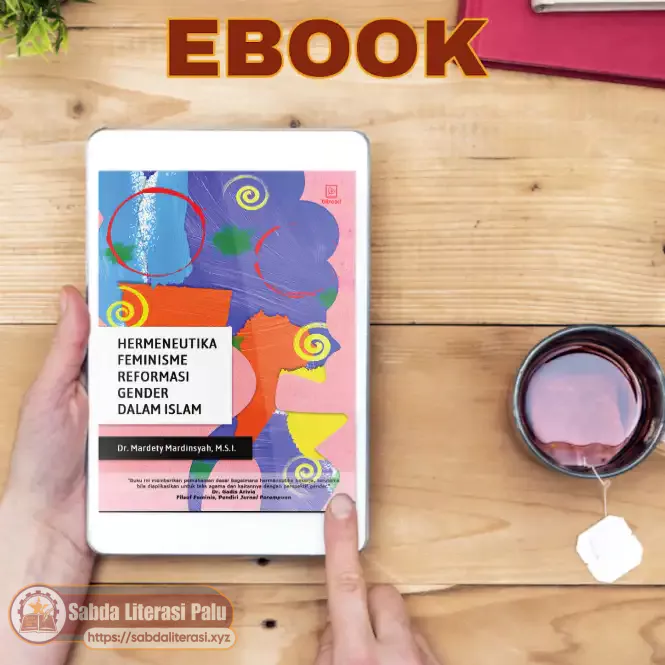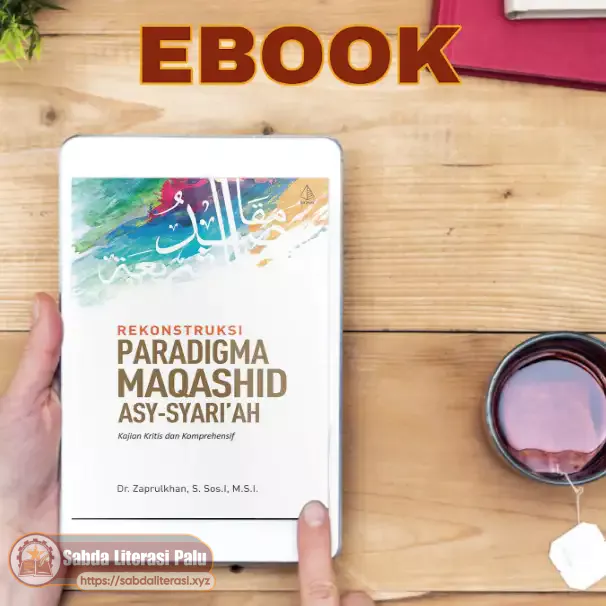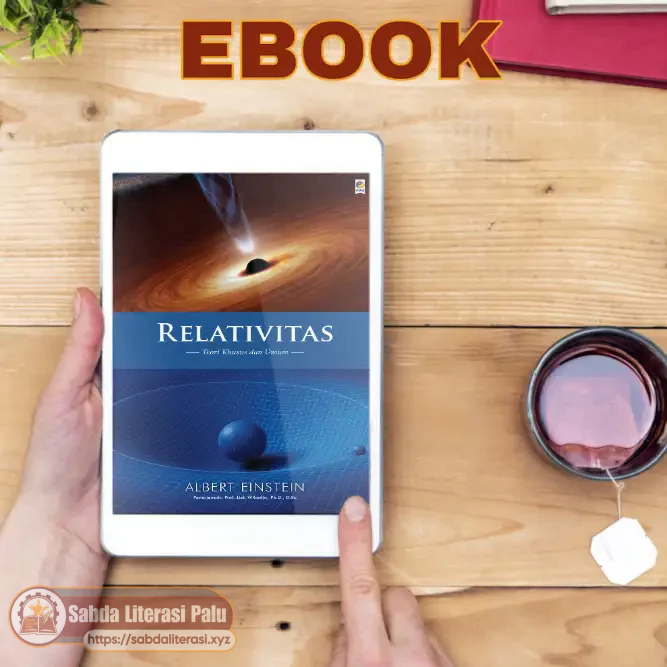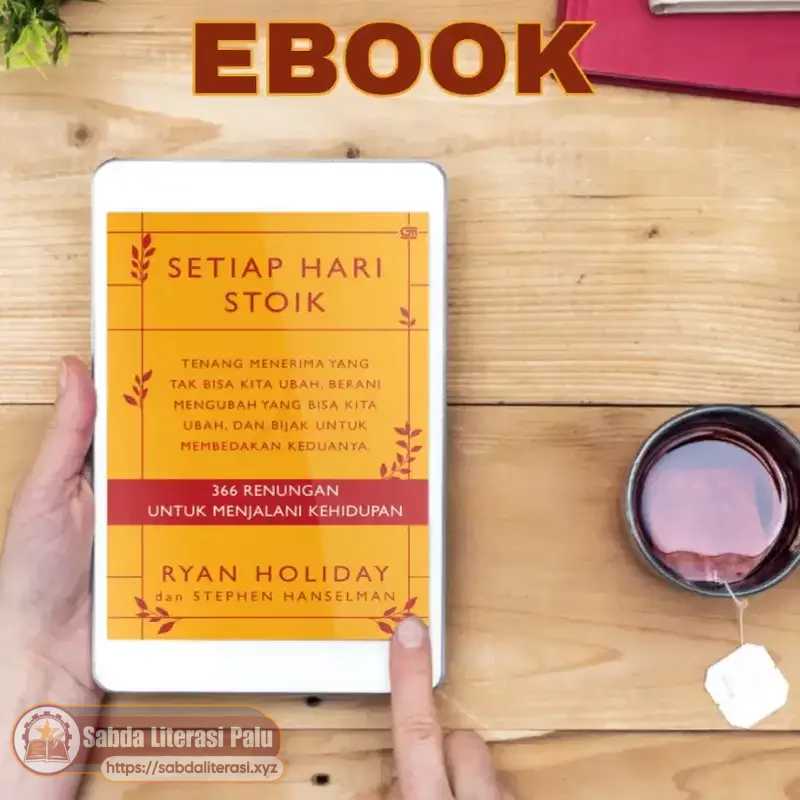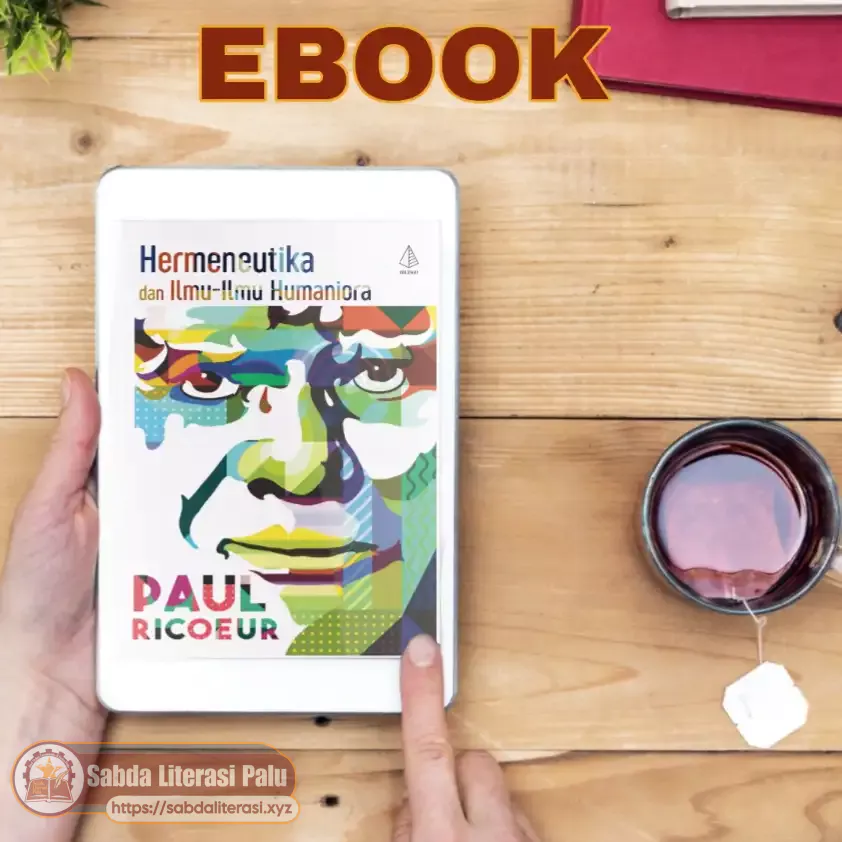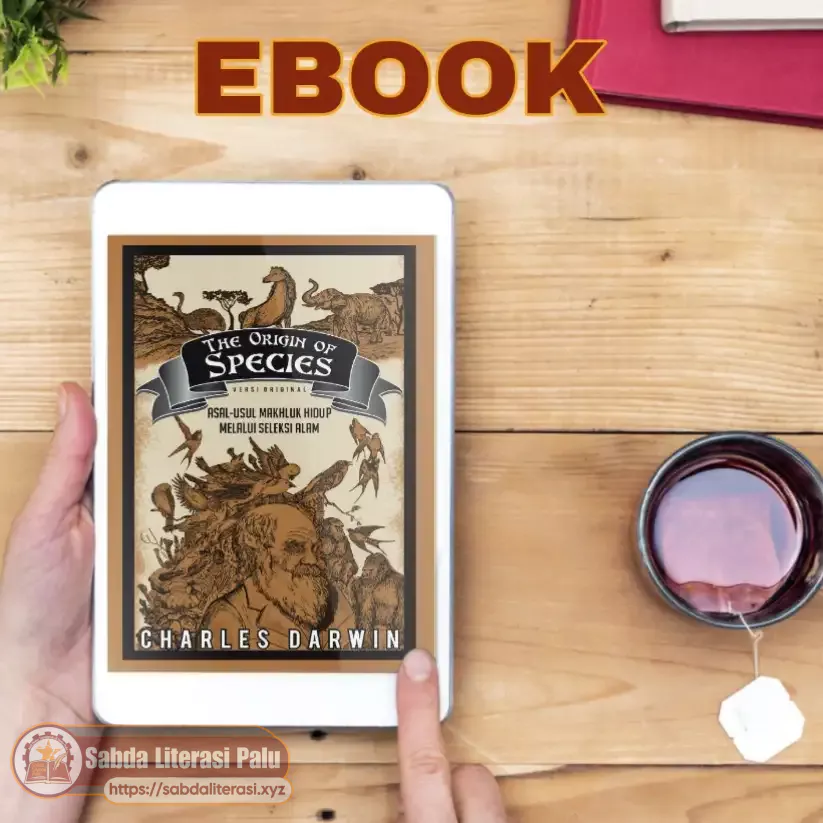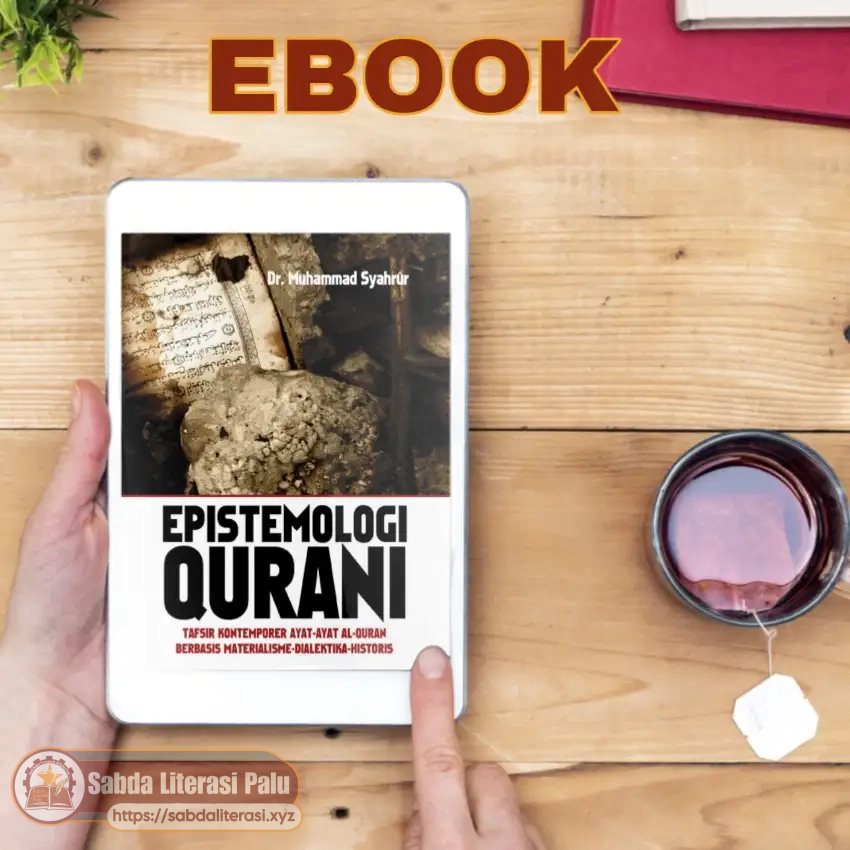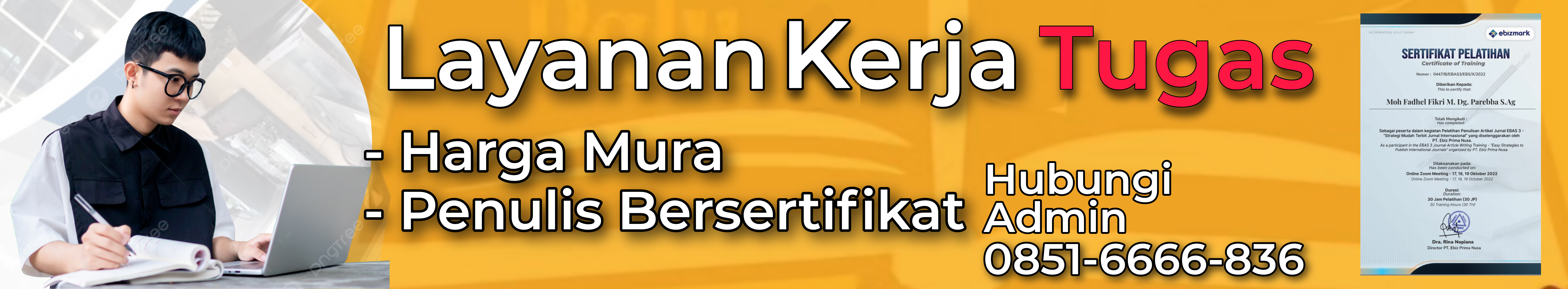|
| Content Created with the help of AI |
Daftar Isi
Ada saat-saat ketika absurditas politik mencapai puncaknya. Ketika seorang guru yang setiap hari mendidik generasi bangsa harus mengais rezeki tambahan dari bimbingan belajar murahan, sementara seorang anggota dewan bisa membawa pulang ratusan juta rupiah hanya dengan duduk di ruang sidang yang lebih sering kosong ketimbang terisi. Di situ kita tidak lagi sekadar melihat jurang kesenjangan ekonomi, melainkan juga jurang moral. Negara, yang seharusnya hadir sebagai penjamin keadilan, justru berubah menjadi mesin distribusi privilese bagi segelintir elit.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pernah melontarkan kalimat yang kini jadi simbol dari ironi itu: “Apakah semua harus ditanggung negara?” Kalimat ini merujuk pada rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia. Ia menyoal, seakan-akan pendidikan adalah beban fiskal, bukan kewajiban konstitusional. Padahal, Pasal 31 UUD 1945 dengan terang menyebut bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, dan negara wajib membiayainya. Jika sebuah negara masih meragukan tugasnya dalam mendidik rakyatnya, apa arti republik itu sendiri?
Lebih jauh, Sri Mulyani dinilai tidak memahami spirit dari UUD 1945. Pernyataan itu bukan sekadar kekeliruan teknis anggaran, melainkan indikasi bagaimana elite negara memandang pendidikan hanya dari sisi angka, bukan sebagai ruh dari kehidupan berbangsa. Guru dan dosen seharusnya dimuliakan, tetapi kenyataan yang kita lihat justru mereka diperlakukan seperti profesi kelas dua. Sementara di seberang sana, anggota DPR hidup dalam kenyamanan yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh kebanyakan rakyat kecil.
DPR sebagai Simbol Kemewahan Absurditas
Jika pendidikan saja masih dipandang sebagai beban, maka yang terjadi di parlemen adalah kebalikannya: kemewahan dianggap sebagai kewajaran. Gaji anggota DPR bisa menembus Rp230 juta per bulan. Jumlah ini bukan hanya jauh dari kata wajar, tetapi sudah melampaui batas nalar. Sementara guru mempertanyakan apakah ia sanggup membayar kos di kota, seorang wakil rakyat bisa menambahkan koleksi jam tangan mewah atau kendaraan barunya tanpa berpikir dua kali.
Perbandingan ini memukul kesadaran kita. UMR Jakarta hanya Rp5,39 juta. Artinya, satu anggota DPR setara dengan 42 pekerja yang hidup pas-pasan di ibu kota. Di Banjarnegara, selisihnya lebih menyakitkan: 105 kali lipat. Apa artinya? Seorang anggota DPR yang sering kali hanya muncul saat rapat paripurna untuk mengangkat tangan, dibayar setara dengan seratus lebih pekerja yang setiap hari bekerja keras untuk sekadar bertahan hidup.
Yang lebih tragis: produktivitas DPR tidak pernah sebanding dengan kemewahan yang mereka nikmati. Hingga Agustus 2025, hanya empat dari 47 RUU yang berhasil disahkan. Bayangkan: empat produk hukum dengan biaya Rp1,6 triliun setahun untuk menggaji 580 anggota dewan. Itu bukan lagi inefisiensi; itu pengkhianatan terhadap logika, terhadap akal sehat.
Absurd, kata Camus, adalah ketika manusia mencari makna di dunia yang justru diam, tidak menjawab. Dan absurd politik kita adalah ketika rakyat menunggu keadilan dari parlemen, tetapi yang muncul hanyalah daftar panjang tunjangan: tunjangan perumahan Rp50 juta, tunjangan komunikasi Rp15 juta, perjalanan dinas, bahkan beras yang dibayar puluhan juta. Seolah-olah fungsi representasi telah diganti dengan fungsi konsumsi.
Di sini absurditas menjadi telanjang. Negara ragu membiayai pendidikan, tetapi sama sekali tidak ragu membiayai kenyamanan elit politik. Rakyat diminta bersabar dengan alasan defisit anggaran, sementara parlemen hidup dalam surplus fasilitas.
Krisis Moral dan Citra DPR
Kemewahan tanpa moral hanya akan melahirkan kehinaan. Dan itulah yang kini tampak jelas dari wajah parlemen. Bukan hanya angka gaji yang mencolok, melainkan juga perilaku anggotanya yang semakin mempertegas jarak dengan rakyat.
Ambil contoh Eko Patrio. Di saat publik marah atas kinerja DPR, ia berjoget di ruang parlemen lalu menanggapi kritik dengan video parodi. Bagi sebagian orang, itu mungkin dianggap jenaka. Tetapi bagi rakyat yang sedang dihimpit harga beras, listrik, dan biaya sekolah anak, joget di gedung wakil rakyat adalah penghinaan. Ia bukan sekadar tindakan personal, melainkan simbol betapa lembaga itu telah kehilangan wibawa.
Belum kering luka itu, muncul Ahmad Sahroni yang menyebut rakyat “tolol” hanya karena ada seruan membubarkan DPR. Ironisnya, pernyataan itu keluar dari mulut seorang politisi yang kekayaannya mencapai Rp328 miliar, dengan koleksi mobil dan properti mewah yang tak habis dihitung. Bagaimana rakyat tidak marah, ketika orang yang dibayar dari pajak mereka justru menertawakan penderitaan mereka?
Dan kemudian Puan Maharani, dengan penuh retorika menyatakan pintu DPR terbuka lebar untuk rakyat. Nyatanya, pagar beton setinggi pinggang berjejer rapat di depan gerbang gedung. Sebuah simbol paling gamblang dari hipokrisi politik: rakyat diminta percaya pada janji keterbukaan, tetapi dihalangi secara fisik dari gedung yang katanya milik mereka.
Filosofisnya, apa yang kita lihat bukan lagi sekadar perilaku individu. Ini adalah krisis moral sebuah institusi. Ketika parlemen tidak lagi menjaga martabatnya, rakyat pun kehilangan alasannya untuk menghormati. Di titik ini, DPR tidak lagi sekadar jauh dari rakyat—ia menjadi musuh rakyat.
Gelombang Perlawanan Rakyat
Di hadapan krisis moral semacam itu, wajar bila rakyat akhirnya turun ke jalan. Absurditas yang terlalu lama dipendam selalu mencari salurannya. Dan ia menemukan bentuknya dalam gelombang demonstrasi yang meluas pada Agustus 2025.
Tanggal 25 Agustus, ribuan orang memenuhi depan Gedung DPR, menuntut transparansi gaji, membatalkan tunjangan rumah Rp50 juta, bahkan menyerukan pembubaran DPR. Suara yang awalnya terpecah-pecah kini menyatu: rakyat muak dengan parlemen yang hanya tahu menambah tunjangan di tengah defisit negara.
Tak lama berselang, buruh bergerak. Mereka menolak sistem outsourcing, upah murah, sekaligus mendesak pemotongan gaji DPR sebesar 20–30 persen. Perlawanan itu bukan sekadar ekonomi; ia adalah kritik moral. Rakyat kecil yang gajinya hanya cukup untuk bertahan hidup, justru berani menantang wakil rakyat yang hidup dalam kelimpahan.
Dan absurditas itu mencapai puncak tragis pada 28 Agustus. Seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, tewas dilindas kendaraan rantis polisi saat sedang berada dilokasi demonstarn. Nyawanya melayang di tengah represi aparat. Ironi ini begitu telak: rakyat menuntut keadilan, yang mereka dapatkan adalah kekerasan.
Di titik ini, absurditas negara berubah menjadi tragedi yang berdarah. Negara yang seharusnya melindungi, justru membunuh. Demokrasi yang seharusnya memberi ruang bagi kritik, justru menutup rapat dengan pagar beton dan gas air mata. Republik yang seharusnya “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” telah berbalik menjadi teater yang melawan rakyat.
Camus pernah menulis bahwa pemberontakan lahir ketika penderitaan mencapai titik di mana manusia berkata: “Cukup.” Dan itulah yang terjadi. Buruh, mahasiswa, ojol, hingga masyarakat sipil bersatu dalam satu kata yang sama: cukup.
Wacana Pembubaran DPR dan Konservatisme Intelektual
Gelombang demonstrasi besar itu melahirkan satu seruan yang paling kontroversial: pembubaran DPR. Bagi sebagian kalangan, seruan ini dianggap berlebihan, bahkan berbahaya. Ahli-ahli politik buru-buru mengingatkan bahwa tanpa DPR, negara bisa terjebak ke monarki atau otoritarianisme. Bung Mahfud Md, misalnya, menegaskan bahwa seburuk-buruknya negara, tetap lebih baik jika ada DPR.
Pandangan ini, sekilas, tampak bijak. Ia berakar pada sejarah: trauma masa lalu ketika lembaga legislatif dilemahkan, lalu kekuasaan terpusat pada satu tangan. Tetapi sejarah, jika dijadikan dogma, bisa berubah menjadi rantai yang membelenggu imajinasi politik. Kita seakan dipaksa untuk percaya bahwa DPR—betapapun bobroknya—harus tetap ada.
Di sinilah absurditas menemukan bentuk barunya. Rakyat muak dengan DPR, tapi para intelektual meminta untuk bersabar. Rakyat menuntut representasi yang nyata, tetapi dijawab dengan narasi “itu sudah lebih baik daripada tiada sama sekali.” Pertanyaan filosofis muncul: apakah keberadaan yang buruk tetap lebih baik daripada ketiadaan? Apakah kita harus terus menerima institusi yang gagal hanya karena takut pada kekosongan?
Kekakuan berpikir ini menunjukkan konservatisme intelektual. Sejarah memang penting, tetapi masa depan tidak bisa terus disandarkan pada cermin masa lampau. Dunia berubah, teknologi berkembang, dan cara berpolitik pun harus berevolusi. Jika kita terjebak pada pola pikir “asal ada DPR,” maka kita hanya melestarikan absurditas, bukan mengatasinya.
Mungkin inilah saatnya kita membalik pertanyaan. Bukan lagi “bagaimana memperbaiki DPR,” tetapi “apakah masih ada bentuk representasi yang lebih jujur, lebih adil, dan lebih sesuai dengan zaman?”
Demokrasi Digital sebagai Jalan Keluar
Jika absurditas adalah kenyataan yang tidak bisa ditolak, maka solusi lahir dari keberanian untuk menatapnya dan melampauinya. Kita sudah melihat bagaimana DPR hidup dalam kemewahan, sementara rakyat terhimpit dalam kemiskinan. Kita juga sudah melihat bagaimana lembaga itu kehilangan legitimasi moral, hingga rakyat berkata: cukup. Pertanyaannya sekarang: apa yang menggantikan?
Jawaban yang kerap ditolak dengan sinis, justru hadir dalam hal yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari: teknologi digital. Jika negara sanggup menggelar seleksi CPNS dengan jutaan peserta secara daring, mengapa mustahil membangun platform demokrasi digital yang memungkinkan rakyat ikut mengambil keputusan?
Bayangkan sebuah sistem di mana rakyat bisa langsung memilih, menyetujui, atau menolak kebijakan penting. Undang-undang tidak lagi disusun hanya di ruang tertutup Senayan, melainkan melalui forum digital nasional yang transparan, dapat diakses siapa saja, dan diawasi secara independen. Dengan model ini, demokrasi tidak berhenti di bilik suara setiap lima tahun, tetapi hidup setiap hari, setiap pekan, setiap isu yang menyangkut kepentingan publik.
Tentu saja, tantangan besar menanti. Pertama, literasi digital. Tidak semua rakyat Indonesia melek teknologi. Tetapi di sinilah tugas negara. Sama seperti dulu ada program wajib belajar, kini saatnya ada program wajib melek digital. Tidak cukup hanya membangun jalan tol fisik; negara harus membangun jalan tol informasi.
Kedua, keamanan data dan potensi manipulasi. Demokrasi digital akan runtuh jika sistemnya bisa diretas atau dikendalikan oleh segelintir orang. Karena itu, sistem keamanan berlapis harus dikembangkan, dengan badan independen yang tidak tunduk pada pemerintah maupun partai politik.
Ketiga, pemerataan infrastruktur internet. Di banyak daerah, sinyal masih mewah, apalagi akses perangkat. Tetapi ini bukan alasan untuk berhenti. Justru inilah kesempatan mempercepat pemerataan. Demokrasi digital harus berjalan seiring dengan keadilan digital.
Lebih dari sekadar teknis, demokrasi digital adalah transformasi filosofis. Ia menegaskan kembali bahwa republik adalah milik publik. Ia mematahkan mitos bahwa hanya segelintir elit yang mampu memahami hukum dan kebijakan. Ia menolak absurditas representasi yang korup, dengan menghadirkan partisipasi langsung yang egaliter.
Camus pernah berkata bahwa melampaui absurditas bukan berarti menemukan jawaban yang sempurna, melainkan menciptakan cara hidup yang lebih jujur. Demokrasi digital, dengan segala tantangan dan risikonya, setidaknya lebih jujur daripada DPR yang kita miliki hari ini.
Reflektif
Sejarah selalu menyimpan ironi. Ada bangsa yang jatuh bukan karena perang, melainkan karena lembaga politiknya kehilangan martabat. Ada negara yang goyah bukan karena musuh dari luar, melainkan karena elit di dalamnya mengkhianati rakyat. Indonesia hari ini berdiri di persimpangan itu: di satu sisi rakyat menuntut keadilan, di sisi lain parlemen justru larut dalam pesta tunjangan.
Tetapi justru dari absurditas itu, sebuah kesadaran lahir. Rakyat mulai melihat bahwa jalan yang diwariskan masa lalu tidak selalu relevan dengan tantangan hari ini. Bahwa DPR bukanlah satu-satunya bentuk representasi, apalagi ketika representasi itu berubah menjadi lelucon. Bahwa demokrasi bisa menemukan bentuk barunya dalam ruang digital, di mana rakyat terlibat langsung, tanpa perantara yang korup.
Jika republik berarti res publica—urusan publik—maka tugas kita adalah mengembalikan republik kepada publik. Bukan kepada partai, bukan kepada elit, melainkan kepada rakyat yang setiap hari bekerja, membayar pajak, dan mendidik anak-anaknya. Dan cara paling jujur untuk melakukannya adalah dengan membuka ruang partisipasi digital yang luas, transparan, dan akuntabel.
Tentu, demokrasi digital tidak sempurna. Akan ada celah, ada risiko, ada kesalahan. Tetapi bukankah itu lebih jujur daripada melestarikan institusi yang sudah jelas gagal? Bukankah lebih masuk akal membiayai guru daripada membiayai wakil rakyat yang menertawakan kritik? Bukankah lebih sesuai dengan amanat konstitusi jika uang rakyat dipakai untuk mencerdaskan bangsa, bukan memanjakan elit?
Absurd memang, bahwa negara harus diingatkan oleh rakyatnya sendiri akan kewajibannya. Tetapi absurditas bukan akhir, melainkan panggilan untuk bangkit. Dan dalam absurditas ini, kita menemukan harapan baru: sebuah republik yang benar-benar kembali ke tangan publik.
Daftar Pustaka
- Kompas.com, “Sri Mulyani Dinilai Tak Paham Konstitusi Usai Singgung Gaji Guru dan Dosen”, 11 Agustus 2025.
- Kompas.com, “Gaji DPR Ternyata Tembus Rp 230 Juta Per Bulan, Ini Rinciannya”, 26 Agustus 2025.
- Suara Nasional, “Kelakuan Eko Patrio Munculkan Kebencian Rakyat ke DPR”, 22 Agustus 2025.
- Warta Kota, “Sebut Rakyat Tolol! Harta Anggota DPR RI Ahmad Sahroni Jadi Sorotan”, 22 Agustus 2025.
- Suara.com, “Puan Maharani Sebut Pintu DPR Terbuka Lebar Saat Demo, Nyatanya Dipagari Beton Tinggi”, 25 Agustus 2025.
- Berita DIY, “Apa Saja Tuntutan Demo di Jakarta 25 Agustus 2025 Depan Gedung DPR MPR RI”, 25 Agustus 2025.
- Kompas.com, “Apa Saja Tuntutan Buruh di Demo 28 Agustus 2025”, 28 Agustus 2025.
- Tribunnews.com, “Media Asing Sorot Demo di Jakarta, Ojol Tewas Dilindas Polisi Picu Aksi Lebih Besar”, 29 Agustus 2025.
- Tirto.id, “Rangkuman Demo 28 Agustus 2025 di Jakarta, Ada Korban Jiwa”, 29 Agustus 2025.
- CNN Indonesia, “Gelombang Demo Pecah di Berbagai Daerah 28 Agustus 2025”, 29 Agustus 2025.